Peranakan
 Apa yang mempersamakan bakpia, nasi campur, dan lumpia? Banyak hal, namun kalau dilihat dari asal-usul kebudayaan tempat ketiga makanan itu berkembang, kebudayaan Tionghoa peranakan adalah yang mempersamakannya.
Apa yang mempersamakan bakpia, nasi campur, dan lumpia? Banyak hal, namun kalau dilihat dari asal-usul kebudayaan tempat ketiga makanan itu berkembang, kebudayaan Tionghoa peranakan adalah yang mempersamakannya.Istilah "peranakan" sendiri muncul ketika gelombang migrasi terakhir kaum Tionghoa terus berdatangan ke Nusantara dari Tiongkok daratan di awal abad 20. Untuk membedakan Tionghoa totok yang baru tiba dengan Tionghoa generasi kedua atau ketiga, timbulah istilah "peranakan" untuk para generasi kedua-ketiga tersebut. Perlu diketahui, ada tiga gelombang besar suku Tionghoa datang ke bumi pertiwi. Yang pertama terjadi pada sekitar abad 15 (Laksamana Cheng Ho datang ke Indonesia juga pada masa itu). Yang kedua adalah ketika terjadi masa perang opium di daratan Tiongkok pada awal 1800-an. Yang terakhir pada awal abad 20.
Selain itu, Tionghoa peranakan biasanya memiliki darah campuran dengan penduduk setempat. Hal ini terjadi karena imigrasi gelombang pertama, kebanyakan yang berimigrasi adalah pria. Saat mereka menetap, mereka memilih untuk mengawini perempuan setempat.
Buku Politik Tionghoa Peranakan di Jawa adalah satu dari sedikit buku yang mengulas sepak terjang kaum Tionghoa peranakan, dengan segala masalah politik di belakangnya. Leo Suryadinata, sang penulis yang mengajar di National University of Singapore, sengaja mengulas sepak terjang kaum Tionghoa peranakan hanya di pulau Jawa antara masa awal kebangkitan nasional hingga masa kemerdekaan Indonesia karena pada masa itu kaum Tionghoa peranakan ini terpecah menjadi tiga bagian.
Mari kita simak lebih lanjut. Perlu diingat bahwa pada awal abad 20, politis etis negri Belanda sedang hangat-hangatnya sehingga menginginkan adanya perwakilan dari kaum Tionghoa dan pribumi masuk dalam Dewan Rakyat (Volksraad). Di sisi lain, kaum nasionalis Tiongkok di daratan mengeluarkan aturan bahwa setiap orang Tionghoa di luar negri Tiongkok tetaplah warga negara Tiongkok. Bisa ditebak, kaum Tionghoa peranakan terpecah antara menjadi warga yang tunduk kepada ratu di negri Belanda atau tetap berafiliasi dengan tanah leluhur. Kaum yang berafiliasi kepada tanah leluhur berada di bawah bendera Sin Po, sedangkan yang menganggap dirinya warga negara Hindia Belanda berada di bawah panji Chung Hwa Hui (CHH).
Jaman terus bergulir, dan kedua pihak ini tidak pernah satu kata. Semuanya menjadi kompleks ketika masa-masa revolusi yang makin menghangat dengan semangat Indonesia merdeka. Dari kaum peranakan, timbulah pula kaum Tionghoa yang menginginkan Indonesia merdeka. Mereka membentuk partai yang dinamakan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tahun 1932. Bagi mereka, kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang harus diperjuangakan kaum Tionghoa karena di sinilah tempat mereka berpijak. Bukan negri Belanda yang nun jauh di sana, bukan pula daratan Tiongkok.
Ketiga kelompok ini memiliki basis pengikut di beberapa kota. Kaum Sin Po sangat kuat di Batavia. Mudah ditebak, Batavia saat itu sudah sangat kosmopolitan dan kebanyakan pendatang totok yang baru tiba sampai di Nusantara melalui Sunda Kelapa. Tak heran pengaruh Tiongkok sangat kuat di kota itu. Kaum CHH kuat di Semarang. Tak lain karena kebanyakan yang tinggal di sana adalah peranakan yang sudah tiga generasi menetap sehingga sangat kuat keterikatan dengan Hindia Belanda. Di Surabaya PTI kuat karena banyak pergerakan kaum muda pribumi yang menginginkan kemerdekaan timbul di kota itu. Tiada heran kaum Tionghoa di sana banyak terbawa arus kuat itu.
Buku yang diterbitkan Sinar Harapan tahun 1986 ini memang lebih kuat mengulas unsur politik. Persinggungan dengan ranah kebudayaan hanya disinggung untuk melengkapi uraian politik. Sedikit contoh dari yang diulas, di buku ini ditulis bahwa perempuan kaum peranakan biasanya memakai kebaya seperti perempuan pribumi.
Dibanding buku Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa karya Ong Hok Ham yang lebih mengulas unsur kebudayaan, buku ini sedikit hambar. Maklum, ditulis untuk kepentingan studi politik. Beda dengan tulisan Pak Ong yang memang dasarnya tukang makan, sehingga isi bukunya serasa memesan semeja penuh masakan babah (istilah kuliner untuk Tionghoa peranakan). Tapi buku karya Leo Suryadinata ini membuka pemikiran bahwa dari kaum Tionghoa muncul pula pergerakan Indonesia merdeka.


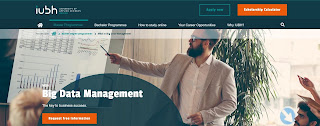
Comments