Djogdja
 Tulisan ini akan sedikit aneh, karena memulai sesuatu cerita tentang kota tapi dimulai dengan cerita kota lain.
Tulisan ini akan sedikit aneh, karena memulai sesuatu cerita tentang kota tapi dimulai dengan cerita kota lain.Begini, akhir pekan lalu aku pergi ke kota Gold Coast, sebuah kota di pesisir timur Australia. Sebenarnya bukan liburan yang terlalu menarik, sebab hujan turun membuat beberapa rencana melihat tempat-tempat menarik terpaksa dibatalkan. Di tengah keadaan yang membosankan itu, ketika aku sedang mencoba berjalan-jalan di tepi pantai sambil mengambil beberapa foto dengan kamera Nikon keluaran tahun 1980, ada sepasang muda-mudi kulit putih yang tersenyum melihatku. Tadinya aku pikir mereka mabuk, karena mereka menggenggam botol bir.
Tiba-tiba sang pemudi menghampiri aku dan berkata,"Kamu bisa berbicara Bahasa Indonesia?". Singkat cerita, setelah aku sedikit terkaget-kaget dengan kefasihannya berbahasa Indonesia, dia adalah pemudi asal Jerman, yang pernah beberapa waktu tinggal di Indonesia. Ternyata dia mengetahui bahwa aku berasal dari Indonesia dengan melihat kausku yang bertuliskan "Djogdja Tempoe Doeloe".
Lalu kami bercakap-cakap tentang Indonesia, tentang Jerman, tentang Australia, dan tentu saja tentang Yogyakarta, atau Djogdja sebagai nama panggilan, atau Yojo sebagai nama yang penduduk asli sebut. Setelah beberapa percakapan yang lumayan panjang dengan sang pemudi yang bernama Nadine dan pacarnya yang asli Australia dan sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, kami saling bertukar alamat surat elektronik dan berjanji untuk saling menghubungi bila salah satu berkunjung ke negara masing-masing.
Entah mengapa, setelah itu pikiranku banyak berada di Djogdja, bukan di Goald Coast. Tiba-tiba suasana Djogdja di pagi hari, ketika ibu-ibu berkebaya beriringan ke pasar mengendarai sepeda memenuhi seluruh isi kepalaku. Atau suasana gang-gang sempit di sekitaran Taman Sari terasa begitu dekat di depan mata. Keriuhan Jalan Malioboro mengingatkanku pada gelang seharga 500 rupiah yang dijajakan di sepanjang jalan itu, yang pernah aku berikan pada seorang gadis manis yang aku puja di kala sekolah tingkat pertama dulu. Juga bau gudeg dan teh nasgitel (panas, legi, kentel) membuat perutku ingin segera kembali ke kota itu.
Sebenarnya aku tidak pernah lama berada di kota itu. Kota itu hanya kota asal ibuku, dan bila aku mengunjungi kota itu, itu pasti hanya untuk berlibur mengunjungi sanak kerabat. Tapi entah mengapa, setiap mengunjungi kota itu, aku selalu merasa berada di sebuah kota tempat aku ingin berada. Seperti pemuda yang melewati masa akil balik, dan melihat bayangan dari seorang perempuan dewasa yang ingin dinikahi di saatnya nanti.
Anda tahu tentang penerbit buku Lonely Planet? Lonely Planet adalah penerbit buku yang mengkhususkan diri menerbitkan buku-buku tentang perjalanan di seluruh dunia dengan sangat mendetail. Buku-buku yang diterbitkan Lonely Planet menjadi sahabat bagi para pelancong bertas punggung (backpacker) atau wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat wisata di penjuru dunia dengan tidak mau tergantung pada biro perjalanan wisata. Baru-baru ini mereka baru menerbitkan buku yang berjudul The Cities Book: A Journey Through The Best Cities In The World. Di buku itu, Lonely Planet mengeluarkan rekomendasi 200 kota-kota terbaik di dunia yang menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta berada di dalamnya, dan satu-satunya yang berada di Indonesia.
Kembali ke Nadine, dia bercerita bahwa ia menyukai kota seperti Djogdja daripada kota-kota modern seperti yang ada di Australia. Baginya kota modern menjadi terlalu membosankan untuk dinikmati. Tak ada kejutan-kejutan yang membuat hidup terasa indah untuk dijalani. Di kota-kota di Indonesia, ia bisa merasakan kehangatan dan situasi yang kadang membuat semuanya terasa begitu nyata, membumi, dan hidup.
Membuat aku begitu menginginkan berada di kota itu. Saat ini.


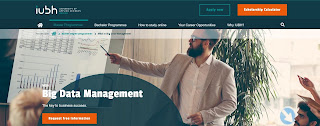
Comments
yupita
salam kenal juga mbak